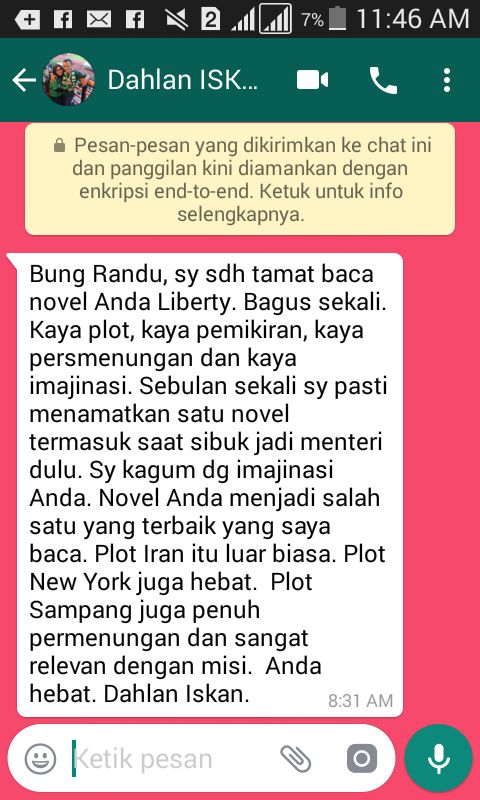Suatu hari di awal tahun 2016, saya bersama Sandi Firly berada di ruang baca Sainul Hermawan. Seperti biasanya kami bergunjing tentang banyak sekali topik, mulai dari bidang yang menjadi minat kami, sastra – , politik, bahasa dan sejarah. Lalu Sainul, kritikus sastra dan dosen di Universitas Lambung Mangkurat menantang saya: Kenapa tidak membuat novel tentang sejarah Lambung Mangkurat?
Saya tertegun. Saya akui, saya sudah lama tergoda untuk menulis novel Lambung Mangkurat. Ada banyak sekali pertimbangan dan satu yang agak personal: karena tahun 2015 dan 2016 adalah tahun yang sangat santai. Saya bisa tidur seharian dan tak menulis apapun selain status facebook dan kadang-kadang menjadi kolumnis gadungan di Koran. Dalam standard kemalasan yang normal, saya harusnya sudah lama terlempar dari jajaran mereka yang disebut penulis (baik yang produktif, maupun yang tidak). Bahkan, jika pun ada yayasan yang menganugerahkan award sebagai penulis paling malas di Indonesia, saya mungkin tak akan mengambil awardnya – saya terlalu malas.
Untunglah, meski setahun tak menulis novel, ada juga naskah saya yang terbit di tahun itu. Sebuah novel semi autobiografi saya berjudul Beranda Angin. Meski tak mencapai apa yang disebut para penjual buku sebagai sebagai best-seller, penjualannya lumayan karena ludes di beberapa toko buku. Tentu saja, di Kalimantan.
Lalu apa? Saya tidak memiliki naskah lagi. Dan, jika ingin bertahan di dunia kepenulisan yang keras-keras manja ini, saya harus bangkit dan mulai menulis. Kemalasan ini harus dilawan dengan sesuatu yang agak radikal, jika boleh dikatakan saya harus bangkit dengan menggarap penulisan naskah novel yang tak biasa. Saat mendengar Sainul Hermawan mengharapkan saya untuk menulis Lambung Mangkurat, saya mulai bersemangat.
Sayangnya untuk menjadi penulis, semangat saja tidak cukup. Kita juga ternyata harus menulis. Segera setelah kembali dari rumah itu, saya dengan cepat melupakan tekad untuk menulis tentang Lambung Mangkurat dan segera kembali ke siklus tidur, kerja-fesbukan, jalan-jalan, yang meski meresahkan, tetapi selalu nyaman.

Nanti, setelah Nisrina Lubis dari penerbit Diva Press menawarkan saya sebuah proyek penulisan novel budaya di akhir tahun itu, gairah saya menulis terpantik kembali. Saya mengajukan naskah yang mustahil itu dengan beberapa alasan yang akan saya jelaskan. Dan, penerbit setuju.
Mereka memberikan saya waktu enam bulan. Sangat longgar sebenarnya. Saya mengira, saya bisa menyelesaikan naskah Lambung Mangkurat setidaknya dalam empat bulan saja.
Tapi, ada sesuatu yang mengiringi setiap sesumbar saya. Sesuatu bernama ketakutan. Saya takut, saya tak akan bisa menuliskan Lambung Mangkurat. Secara teknis, ini naskah yang berat. Setahu saya tak ada yang pernah menuliskannya kecuali hanya sepintas-sepintas. Sekilas di sini, sedikit di sana. Tapi, tak ada gambaran utuh tentang siapa sebenarnya Lambung Mangkurat?
Lambung Mangkurat adalah jarum yang patah dalam tapak waktu sejarah Banjar. Sosoknya melayang-layan di langit mitos dan realitas dan tetap menghantui para peminat sejarah Banjar hingga saat ini. Banyak yang mempercayai bahwa Lambung Mangkurat tak pernah benar-benar ada, meski hal ini tentu saja akan menjadi lucu karena sudah terlanjur banyak tempat, atau jalan, yang memakai namanya. Universitas paling tua di Kalimantan bahkan meminjam namanya: Universitas Lambung Mangkurat.
Kalau memang ada, siapa dia? Kontroversi yang mengiringi kehadirannya dalam sejarah Banjar tak lebih jelas dari sikap dan kebijakan politiknya. Dalam beberapa referensi yang saya baca, dia adalah seorang mahapatih, anak dari pendiri Negara Dipa dan telah membawa Kerajaan itu melalui waktu-waktu tersulit. Dalam perbicangan di kalangan tertentu, dia justru adalah penjahat dan gembong yang tega melakukan kekejaman apapun, bahkan membunuh keluarganya sendiri.
Umumnya, mereka yang ingin mengkaji tentang Lambung Mangkurat harus membaca Hikayat Banjar dan Kotawaringin dalam kajian filologi Johannes Jacobus Ras yang juga terbagi dalam dua resensi yang membingungkan: I dan II. Ada perbedaan yang sangat mencolok dalam dua resensi ini dan penyimpangan-penyimpangan antara satu dengan yang lain membuat saya sakit kepala.
Kelak, saya juga membaca Tutur Candi karya sastra kuno yag dipinjamkan sahabat saya Aliansyah Jumbawuya. Agak sulit karena ceritanya kental dengan dunia yang dibentuk oleh kesaktian tokoh-tokohnya. Saya tak ingin cerita ini menjadi sebuah legenda rakyat. Saya ingin menulis novel.
Mungkin jawaban mengapa Lambung Mangkurat begitu sulit dipahami, karena tradisi oral dalam masyarakat Banjar begitu dominan. Kisah-kisah bersambung dari generasi ke generasi dan menyebar dari mulut ke mulut. Masyarakat punya kecenderungan kagum kepada sosok tertentu yang kemudian dilekatkan dengan kemampuan adikodrati, ada yang mengendarai buih, bertapa menaklukan naga, terbang dan menikah dengan peri di kahyangan…. Dalam masyarakat seperti itu, mitos selalu mengambilalih setiap fakta dan kebenaran yang tersisa selalu lebih membingungkan: Mengapa ada Iskandar Zulkarnain dan Nabi Haidir dalam sebuah kerajaan Hindu-Banjar? Kenapa bahkan saat mengawini putri-putri itu, mereka tak menyebarkan islam saja?
Karena itu, tidak heran dalam tiga bulan pertama saya mandek di bab-bab awal. Setiap malam, usai kerja, saya membuka komputer dan sembari menatap langit-langit berharap hantu Lambung Mangkurat bisa terperangkap di dalam layar Microsoft word. Saya tertidur dengan ketakutansemakin berlipat.
Dua bulan jelang deadline, saya baru mulai intens menuliskannya setelah meyakini bahwa saya tak bisa menyajikannya dengan sempurna. Pendekatan saya adalah alter-history, genre yang setahu saya masih jarang dalam penulisan fiksi sejarah. Di luar negeri, genre ini dipakai Robert Harris dalam Father Land -nya. Saya berharap, bisa melepaskan beban menulis sejarah sekaligus bisa melenggang bebas dari kejaran para sejarawan yang menuntut kebenaran faktual dari kisah ini.
Jadi, demikianlah, pada hari yang gelap di awal April kemarin, Microsoft word saya save, laptop saya tutup. Aneh sekali, saat menyadari dengung dari mesin itu telah terhenti. Seperti biasa, usai menyelesaikan naskah, saya segera tenggelam dalam depresi.
Tapi, dalam sehari, menikmati sedikit penghiburan bersama teman-teman, makan mie, mendengarkan musik, saya mulai rindu pada Lambung Mangkurat, pada Dulur, pada Putri Junjung Buih, pada Patmaraga, pada Sukmaraga, pada Gajah Mada, dan beberapa tokoh lain. Mereka telah menemani saya selama beberapa bulan ini, menjadi sosok yang nyata, yang memiliki kelebihan, kelemahan, yang melakukan pengorbanan, yang memiliki ambisi, memendam sakit hati, mendambakan kerinduan, penerimaan, dan juga cinta.
Saya berharap karya ini bisa diterima sebagaimana sebuah cerita adanya. Murni cerita. Sainul Hermawan mengatakan dulu kepada saya: “Kisah ini mungkin bukan sejarah tetapi setidaknya akan membuat generasi kita akan lebih penasaran dan kemudian mulai membaca kembali sejarahnya sendiri.”()
Negara Dipa, 1938 di Tahun Saka
Randu Alamsyah